Orang Kaya, Anak Orang Kaya dan Perkembangan Musik Indonesia
Mendiskusikan kontribusi orang kaya atau anak orang kaya dalam sejarah musik Indonesia pada era 1970–2000-an merupakan topik yang sangat menarik dan sering kali luput dari perhatian. Dalam banyak kasus, keberadaan mereka justru menjadi katalis penting bagi lahirnya karya-karya musik yang visioner dan berani menembus batas zamannya. Seorang kawan saya pernah berkelakar semasa kuliah, “Indonesia butuh lebih banyak anak orang kaya yang gila musik agar punya produksi karya yang esensial dan diakui di peta musik dunia.” Kalimat itu terdengar sederhana, namun ada benarnya: tanpa dukungan modal dan keberanian bereksperimen dari kalangan yang memiliki privilese, banyak proyek musik monumental mungkin tak akan pernah lahir.
Di dekade 1970-an, misalnya, muncul sosok Guruh Soekarnoputra—anak Presiden Soekarno—yang menjadi pionir dalam menggabungkan musik tradisional Indonesia dengan sentuhan progresif Barat melalui proyek legendaris Guruh Gipsy. Ia menggandeng para musisi muda berbakat seperti Chrisye dan Keenan Nasution, melahirkan album yang hingga kini dianggap salah satu tonggak penting dalam sejarah musik Indonesia modern. Guruh tak hanya membawa visi artistik, tetapi juga menunjukkan bagaimana privilese dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan budaya, bukan sekadar menumpuk kekayaan pribadi.
Kisah serupa juga tampak dalam perjalanan band Shark Move yang merilis album fenomenal Ghede Chokra’s pada tahun 1970-an. Konon, produksi album tersebut mendapat dukungan finansial dari seorang juragan kain di Tanah Abang yang mengagumi idealisme dan musikalitas grup tersebut. Dukungan seperti ini memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi, bila berpadu dengan visi seni, bisa menghasilkan karya yang melampaui zamannya. Bahkan pada era 1990-an, spirit semacam itu masih terasa lewat proyek-proyek eksperimental seperti 4 Through the Sap (1993), yang berani menabrak pakem industri musik komersial saat itu.
Namun, salah satu contoh paling fenomenal adalah Kantata Takwa pada awal 1990-an, sebuah proyek kolosal yang menyatukan kekuatan seniman besar seperti Iwan Fals, Sawung Jabo, dan WS Rendra, di bawah dukungan konglomerat idealis, Setiawan Djody. Kantata Takwa bukan sekadar konser atau album, melainkan gerakan budaya yang menyuarakan kegelisahan sosial dan politik bangsa melalui musik. Di sinilah terlihat bagaimana peran orang kaya yang memiliki visi sosial bisa mengubah musik menjadi alat perlawanan dan refleksi intelektual.
Dari deretan contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa modal bukan sekadar faktor ekonomi, melainkan jembatan untuk memungkinkan eksplorasi kreatif yang lebih luas. Orang kaya atau anak orang kaya yang mencintai musik punya kesempatan untuk membuka ruang eksperimentasi tanpa terikat pada tekanan pasar. Mereka bisa menjadi patron seni modern, seperti yang terjadi pada masa Renaissance di Eropa, di mana para bangsawan menjadi pelindung bagi seniman besar.
Sayangnya, di era musik digital saat ini, peran semacam itu mulai memudar. Banyak kalangan berada di lingkar kemapanan ekonomi lebih memilih menginvestasikan kekayaannya pada bisnis yang cepat berputar ketimbang mendukung proyek seni yang berdampak panjang. Padahal, jika melihat ke belakang, musik Indonesia bisa tumbuh besar dan berani justru karena ada keberanian dari kalangan berpunya untuk membiayai karya yang “tidak komersial”.
Mungkin sudah saatnya kalangan elite baru di Indonesia kembali memaknai peran sosial mereka dalam dunia musik. Dukungan terhadap musisi independen, pendanaan riset musik tradisi, hingga pembangunan studio rekaman berkualitas tinggi bisa menjadi bentuk nyata kontribusi. Seperti halnya Guruh Soekarnoputra atau Setiawan Djody, para “anak orang kaya yang gila musik” bisa kembali menjadi motor penggerak lahirnya era baru musik Indonesia yang bukan hanya populer, tetapi juga berpengaruh secara global.

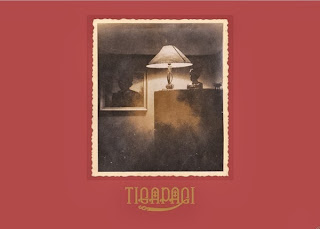
Comments
Post a Comment